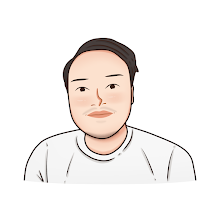Saat
aku tengah menunggu angkot sambil membaca Al Qur’an di smartphone-ku, ada
seseorang yang menepuk pundakku. Aku spontan menoleh. Seseorang tersenyum
kepadaku. Cukup familiar, tapi siapa? Sepertinya aku pernah mengenalnya.
“Hei Bro, masih ingat gue nggak?”
Aku
mengernyitkan dahi. Wajahnya tidak asing. Aku memang seperti mengenalnya. Aku
berusaha membuka kembali memoriku. Mencoba mencari-carinya di sudut otakku.
“Herdy?”
“Ah, jangan belagak kaget lu Bro.”
Lelaki bernama Herdy spontan memelukku dan menepuk punggungku. Salam darinya
yang masih aku ingat.
“Apakabar kau, Her?”
“Seperti yang lu lihat. Elu nggak
jauh beda ya dengan masa SMA dulu. Tetep alim,” kata Herdy melihat penampilanku
dari atas ke bawah. Mungkin karena Herdy melihat baju koko-ku.
“Ngomong-ngomong lagi ngapain kau di
kota ini? Bukannya lulus SMA, kau kuliah di luar kota?”
“Gue juga kangen dengan kota ini.
Makanya gue sempetin main. Kuliah lu gimana? Jangan-jangan elu udah lulus ya?
Diantara kita bertiga, ‘kan elu yang selalu jadi bintang kelas. Gila lu ya
dulu. Juara tapi nggak ngajak gue dan Wisnu.”
Aku
mendadak ingat Wisnu. Saat SMA, aku, Herdy, dan Wisnu adalah tiga sekawan yang
ke mana-mana selalu bersama. Pertama kenal saat masa orientasi, persahabatan
kami begitu kental. Bahkan tiga tahun kami selalu sekelas. Baru saat lulus SMA,
kami berpisah. Aku melanjutkan kuliah di kota kecil ini sementara Herdy dan
Wisnu kuliah di tempat yang sama di luar kota.
“Wah.. kalo lu tahu Wisnu sekarang, beuuuh… dia udah sukses, Bro. Wirausahanya
jalan. Keren pokoknya.”
Wisnu
berwirausaha? Baguslah. Diantara kami bertiga, Wisnu yang paling kalem. Tidak
menyangka sekarang jadi wirausaha. “Usaha apa Wisnu?”
"Bisnis bareng istrinya. Butik
khusus pakaian muslim dan muslimah.”
Aku
terbelalak mendengar perkataan Herdy. Wisnu sudah menikah? Bagaimana mungkin
aku tidak tahu?
“Oh iya, gue jadi ingat sesuatu.
Kenapa lu nggak datang ke nikahan Wisnu, Bro? Lu udah kami tunggu-tunggu lho.”
Apa
Wisnu mengundangku di acara pernikahannya? Aku tidak ingat ada undangan dari
Wisnu. Memang untuk beberapa undangan pernikahan, aku sengaja tidak datang
karena kesibukanku di organisasi kampus. Ah, mungkin undangan Wisnu terselip di
daftar undangan yang aku abaikan. Wajar juga Wisnu tidak menghubungiku karena
sejak ponselku hilang, aku ganti nomor. Nomor Wisnu dan Herdy pun ikut hilang
juga.
Angkot sudah terlihat dari ujung
jalan.
“Bro, lu sibuk nggak? Makan dululah.
Kita ngobrol-ngobrol. Udah lama kita nggak ketemu,” kata Herdy.
Aku
melihat jam di tanganku. Masih ada waktu sebelum maghrib datang. Sebenarnya aku
mau langsung pulang. Terlalu sering aku pulang malam mengurus organisasi.
Mumpung sekarang bisa pulang cepat, aku gunakan kesempatan ini untuk segera
pulang sebelum maghrib. Tapi ajakan Herdy, sahabat yang lama tidak bersua, juga
tidak mungkin aku tolak.
Aku pun mengiyakan ajakan Herdy.
[]
“Lu lagi usaha apa sekarang, Bro?”
Tanya Herdy sambil menikmati Ayam Geprek 20 cabenya. Wajahnya sudah basah oleh
keringat. Segelas besar air es bahkan sudah habis setengahnya.
“Aku sibuk organisasi di kampus
aja.” Jawabku singkat.
“Ah, elu dari dulu sukanya main
organisasi terus. Tapi gue nggak heran. Itu ‘kan jiwa elu banget.” Herdy
ngos-ngosan, kepedasan, lalu meminum air es sampai habis.
Beda
dengan Herdy, aku memesan capcay tanpa cabe. Aku tidak suka pedas. Jadi aku
bisa makan dengan santai tanpa perlu megap-megap. Sambil menikmati makanan sore
itu, kami bercerita banyak hal. Kuakui, banyak yang berubah dari Herdy. Gaya
bicaranya tetap ber-elo-gue karena sejak kecil ia memang tinggal di ibukota.
Barulah saat SMA pindah ke kota kecil ini. Dulu, Herdy terkenal yang paling
jahil diantara kami bertiga. Dengan paras tampannya, Herdy banyak berpacaran
dengan cewek, baik yang satu sekolah maupun dari sekolah tetangga. Aku hanya
bisa geleng-geleng kepala melihat track
record sahabatku itu.
Pernah, suatu ketika Herdy jadi mak comblang untukku. Waktu itu ia
menjodohkanku dengan Riana, cewek yang jadi mayoret marching band sekolah.
Siapa yang tidak kenal Riana? Selain cantik, Riana juga ramah terhadap semua
orang, sepanjang yang aku tahu. Mayoret marching band sekolah memang selalu
cantik. Tapi waktu itu aku menolak perjodohan. Aku pikir belum saatnya aku
berurusan dengan hal seperti itu. Lagipula menurutku pacaran itu hanya punya
sedikit manfaat. Lebih baik aku fokus dengan sekolah dan organisasi dulu.
Entah ini cuma perasaanku atau
bukan, aku rasa Riana dulu punya rasa suka kepadaku. Setelah aku menolaknya,
besok hari aku melihat Riana berboncengan dengan cowok penunggang motor gede
dari SMA sebelah. Mungkin aku yang terlalu berlebihan. Sejak penolakan itu,
Herdy tidak pernah sok menjodohkanku.
Herdy banyak bercerita tentang
mimpinya. Dulu ia ingin punya toko yang menjual perlengkapan olahraga. Dan saat
ini, keinginannya sudah terkabul. Membuatku takjub, terkejut, tidak menyangka
dan beraneka rupa rasa lainnya mengetahui fakta itu. Padahal baru empat tahun
kami tidak bertemu, tapi perkembangannya sudah jauh seperti itu. Jujur, aku
merasa kalah olehnya.
Aku kembali melihat diriku sendiri.
Apa perubahan yang terjadi denganku? Sepertinya aku merasa tidak ada perubahan
yang berarti. Aku tetap sibuk di organisasi kampus dan fokus di dalamnya sejak
awal semester kuliah. Mimpiku jadi penulis, ah.. sepertinya belum jadi apa-apa.
Aku sepertinya melupakan mimpiku itu.
“Mana buku-bukumu Bro? Katanya mau
jadi penulis?” Herdy masih ingat saja dengan mimpi yang aku ceritakan saat
kelas X dulu. Aku memang suka menulis. Karangan pendek saja. Beberapa kali
tulisanku muncul di majalah sekolah. Tapi sejak kelas XII, aku mulai jarang
menulis. Puncaknya saat aku mulai memasuki dunia perkuliahan, aku meninggalkan
sama sekali dunia kepenulisan. Aku seperti tersentak oleh pertanyaan Herdy.
“Sabarlah. Nanti kau tunggu saja
bukuku. Kau harus jadi pembeli pertama ya,” kataku sambil tersenyum. Ah, jumawa
sekali aku ini. Bertahun-bertahun tidak lagi menulis, kenapa kata-kataku
terlihat hebat begitu? Bahkan aku sudah lupa kenikmatan menulis.
“Sibuk organisasi itu bagus Bro,
tapi elu jangan lupain mimpi-mimpi elu. Masa empat tahun ini belum ada satu pun
mimpi lu yang jadi nyata? Bukannya gue sombong Bro, tapi empat tahun itu
terlalu lama untuk merealisasikan mimpi kita. Asalkan kita tekun, jangankan
empat tahun. Satu tahun aja bisa jadi lho mimpi kita jadi nyata. Gue udah
ngerasain itu.”
“Demi toko perlengkapan olahraga
yang jadi mimpi gue itu, gue rela berhutang di sana-sini. Gue waktu itu
berpikir masa bodoh. Yang penting mimpi gue harus bisa jadi kenyataan. Dan yang
paling penting, jalan yang gue tempuh nggak melanggar hukum. Gue usaha dan gue
yakin hutang-hutang itu bakalan gue lunasin kelak. Dan Alhamdulillah sekarang
walau toko perlengkapan olahraga milik gue belum begitu besar, tapi
hutang-hutang itu sudah mulai terlunasi.”
Aku terdiam mendengar cerita Herdy
tentang perjuangannya meraih mimpi. Aku habiskan es jeruk di dalam gelasku.
Sepertinya aku terlalu asyik di zona nyaman. Hidupku belakangan ini memang,
sejujurnya kuakui, hanya begitu-begitu saja. Kesibukan memang menyita waktuku,
tapi aku kurang merasakan greget di sana. Entah kenapa. Apa karena aku berjuang
untuk sesuatu yang seharusnya tidak aku perjuangkan? Apa seharusnya aku
memperjuangkan mimpiku saja?
Sudah terlalu lama aku dengan
kehidupanku ini. Apa masih ada waktu? Pertanyaan bodoh. Masih ada atau tidaknya
waktu, hanya Tuhan yang tahu. Sebagai manusia, manfaatkan saja waktu yang ada
untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Melakukan hal untuk merealisasikan
mimpi-mimpi.
Maghrib sebentar lagi datang. Capcay
di piringku sudah tandas. Begitu juga dengan ayam geprek di piring Herdy. Ia
masih kepedasan dengan keringat yang terus mengalir dari dahinya. Aku pun
memutuskan untuk pulang. Herdy ingin menginap di rumahku, tapi sengaja aku
tolak. Bukannya aku tidak ingin Herdy menginap, hanya saja malam ini aku butuh
waktu sendirian untuk merenungkan banyak hal.
Aku masih belum melupakan mimpiku.
Mungkin rasanya akan berat memulai dari awal, tapi pertemuan tidak terdugaku
dengan Herdy, memang sengaja dirancang oleh Tuhan untuk menyadarkanku akan
mimpiku yang nasibnya tidak jelas ini. Rasanya aku malu sendiri mengingat
mimpiku itu. Mimpi yang sudah lama aku lupakan.
Dan di senja ini, aku sepertinya
memang harus menata hati untuk kejutan-kejutan yang tidak terduga. Sebelum
pamit, Herdy memberiku sebuah surat berwarna cokelat dengan sisi-sisi berwarna
merah dan biru. Aku tidak mengerti dengan surat itu, tapi Herdy menyuruhku
untuk membuka surat itu sekarang.
“Kau, menikah?” kataku tidak
percaya. Herdy tersenyum sambil menaikkan sebelah alisnya. Dua minggu lagi.
Ternyata dua sahabatku telah mendahuluiku menemukan pendamping hidup.
Langit semburat kemerahan. Aku lihat
burung-burung beterbangan di ujung sana. Hatiku rasanya teraduk-aduk dengan
kejutan ini. Aku menghela nafas panjang. Kuakui kekalahanku. Saatnya aku mulai
lagi mimpiku. Kalah bukan berarti menyerah. Akan segera aku raih kemenangan itu
agar aku bisa sejajar dengan Herdy dan Wisnu.
Reuni selanjutnya, entah kapan Tuhan
akan mempertemukan, mungkin saat itu kami sudah membawa buah hati
masing-masing. Semoga.[]
Jogja,
22 Oktober 2014