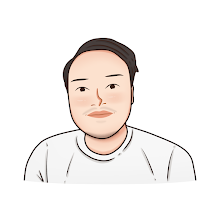16 Maret 2016
Ternyata
satu tahun belum menjadi rentang waktu yang cukup untuk mengenal dan memahami.
Semacam sedih karena kebersamaan selama ini dimaknai seperti apa? Saya pikir
kami sudah saling mengenal, ah.. apa hanya perasaan saya? Kami memang saling
mengenal tapi tidak saling memahami. Benarkah begitu? Apa saya nggak memahami
juga? Saya rasa nggak sepenuhnya begitu.
Semua
ini berawal dari kesalahan yang saya buat. Ya, saya sadar akan kesalahan itu,
tapi semua itu terjadi bukan karena saya sejahat dan setega yang dipikirkan. Ya
Rabb.. jika saya sejahat dan setega itu, hukum saya. Waktu itu, saya sempurna
lupa, bukan sengaja nggak memberitahu. Sama sekali bukan.
Siaran
di dua tempat memang terkadang bikin hectic,
apalagi saat jadwal bertabrakan. Biasanya saat seperti ini solusinya adalah
bertukar jam siaran. Jauh-jauh
hari saya sudah meminta tolong kepada seorang teman untuk bertukar jam siaran.
Minggu pertama saya catat. Minggu kedua ternyata saya lupa mencatatnya. Alhasil
saya lupa.
Hari
itu, saat saya sempurna lupa, saya juga merasa aneh. Kenapa saya nggak minta tukar siaran padahal jadwal saya bertabrakan di dua radio? Hal yang membuat saya
sempurna lupa, siaran di radio B jadi libur karena ditukar di hari lain,
jadinya saya bisa siaran di radio A. Ini yang membuat saya sempurna lupa. Jika
saja waktu itu jadwal di radio B nggak ditukar di hari lain dan benar-benar
bertabrakan dengan jadwal radio A, saya pasti bakal mengingat atau paling nggak
teringatkan dengan janji bertukar siaran jauh-jauh hari itu.
Saya
salah dalam hal ini, tapi teman saya justru juga sengaja membuat kesalahan yang
menyusahkan dirinya sendiri dan akhirnya mencipta sakit di hatinya. Waktu itu,
saya dengan keadaan sempurna lupa tentang janji bertukar siaran jauh hari,
datang ke radio A untuk bersiaran. Teman saya yang seharusnya menggantikan saya
juga sudah datang. Saya yang memang benar-benar lupa, langsung bertanya saat
bertemu dengan teman itu, “Loh, kok masih di sini?”
Waktu
itu memang paginya ada pertemuan. Siangnya ada pawai yang membuat akses menuju
radio A ada yang ditutup. Saya pikir dia masih stay karena hal itu. Teman saya nggak bilang apa-apa, bahkan saat
saya bertanya seperti itu. Barulah saat teman saya pulang, datang sebuah pesan
singkat, “Gus, kita jadi bertukar nggak?”
Saya
bingung. Bertukar apa? Teman saya mengingatkan tentang janji bertukar siaran
jauh hari itu. Seketika saya ingat dan baru menyadari. Saya lupa! Teman saya
hanya bilang, “Kalau nggak jadi bertukar, bilang ya.” Hanya itu yang teman saya
katakan. Saya langsung meminta maaf atas kelalaian yang saya lakukan. Ini
memang kesalahan saya. Saya benar-benar merasa nggak enak.
Hari
berikutnya saat saya bertemu dengannya, sikap teman saya biasa saja. Nggak ada
yang berubah. Sama, seperti biasanya. Hati orang siapa yang tahu? Ternyata
dibalik sikap biasa-biasa itu tersimpan sakit hati. Saya nggak menyadarinya.
Saya pikir masalah kemarin sudah selesai. Kita sudah sama dewasa. Saya pikir
permintaan maaf secara langsung via pesan singkat saat teman saya mengingatkan
janji yang terlupakan, sudah cukup dan semua selesai. All clear. Ternyata dugaan saya salah. Teman saya masih menyimpan
sakit hati karena sikap saya. Hanya saja dia memilih diam dan menceritakannya
kepada orang lain yang memang dekat dengannya.
Saya
sedih. Kenapa dia diam saja? Kenapa saat kejadian itu, saat seharusnya dia
bersiaran dan saya datang, kenapa nggak langsung menanyakan dan semacam mengingatkan bahwa kami bertukar siaran? Apa susahnya bilang
langsung begitu dan bukannya lewat pesan singkat setelah teman saya justru
pulang dengan menelan kekecewaan yang teramat sangat? Ini yang membuat saya
sedih juga greget dengan sikap orang Jawa yang lebih suka memendam.
Saat
saya salah, tolong langsung diingatkan. Apalagi jika kesalahan saya
membawa-bawa orang lain juga. Sakit hati itu tercipta karena sikap teman saya
juga. Kenapa nggak langsung mengatakan saat itu juga? Saya benar-benar lupa
dengan janji bertukar siaran jauh-jauh hari. Saya nggak ingat. Kenapa teman
saya menanyakan saat dia sudah pulang dan melalui pesan singkat? Kenapa?
Saya
memang salah, tapi yang perlu diingat saya nggak sejahat dan setega itu. Jika
memang nggak jadi bertukar siaran, saya pasti bilang. Apa kamu mengerti, Teman?
Satu
tahun ternyata belum membuatmu mengenal saya. Satu tahun mungkinkah belum
membuat saya mengenalmu? Saya nggak merasa seperti itu. Saya merasa ada
kedekatan denganmu. Walau saya nggak memahamimu luar dan dalam, tapi
seenggaknya saya merasa ada kedekatan denganmu, tapi... ternyata kamu belum
bisa memahami selama satu tahun kita mengenal. Maaf... saya nggak menyalahkan
siapapun, saya hanya berusaha introspeksi diri.
Kejadian
ini membuat saya mencatat penting: saat janji telah diucapkan, segeralah
dicatat karena manusia adalah tempatnya lupa.
Buat
teman yang hatinya sakit karena kejadian itu, maaf. Saya benar-benar meminta
maaf. Saya nggak sejahat dan setega itu, nggak bilang kalau nggak jadi tukar siaran. Saya nggak akan pernah melakukan itu. Na’udzubillah... Semoga kamu memang mengerti.
Satu
hal lagi, ini catatan buat siapapun, jika ada ganjalan di hati, katakan saja,
apalagi berhubungan dengan seseorang yang kita kenal, sudah berteman satu tahunan, jika memang masih wajar dikatakan saat itu, katakanlah. Tolong
jangan memendam hal yang sebenarnya sepele jika memang kita tipikal orang yang
suka memendam perasaan.[]
Jogja, 16.03.2016
*untuk
teman saya, saya benar-benar meminta maaf dan semoga kita bisa lebih mengenal dan
memahami